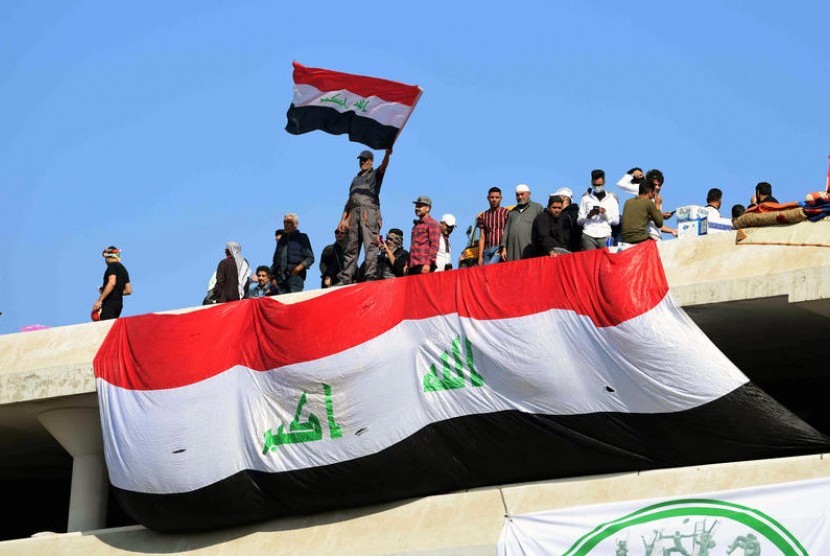REPUBLIKA.CO.ID, BAGHDAD - Pada 28 Juni 2004, Amerika Serikat (AS) menyerahkan kembali kekuasaan kepada rakyat Irak dalam upacara sederhana di Baghdad. Administrator AS, Paul Bremer menyerahkan kedaulatan kepada seorang hakim Irak pada serah terima yang diajukan dua hari dalam upaya mencegah pertumpahan darah.
Bremer terbang ke luar negeri tak lama setelah itu. Kepergiannya mengakhiri 15 bulan kendali AS di Irak.
Perdana Menteri sementara Irak Iyad Allawi, yang menghadiri penyerahan di "Zona Hijau" yang dijaga ketat di kota itu, mengatakan itu adalah hari bersejarah bagi Irak. Kabinet Allawi dilantik pada upacara berikutnya, dan diadakan secara rahasia.
Perdana menteri baru membuat pidato di televisi setelah secara resmi menjabat. "Saya menyerukan kepada orang-orang kami untuk bersatu untuk mengusir teroris asing yang membunuh anak-anak kami dan menghancurkan negara kami," katanya kala itu dikutip laman BBC History, Senin (28/6).
Meskipun kekuasaan kembali ke tangan Irak, Presiden AS George Bush mengatakan, pasukan Amerika akan tetap berada di negara itu selama mereka dibutuhkan. Presiden menambahkan bahwa kehadiran AS juga akan atas permintaan pemerintah sementara yang baru dibentuk.
Sementara Bremer membela alasan negaranya berada di Irak. Dia mengacu pada kuburan yang baru ditemukan di mana ribuan korban rezim Saddam Hussein diyakini dimakamkan.
Bremer sebagai mantan administrator Otoritas Sementara Koalisi mengatakan, siapa pun yang memiliki keraguan tentang apakah Irak adalah tempat yang lebih baik hari ini daripada 14 bulan yang lalu harus turun dan melihat kuburan massal di Hilla. "Siapa pun yang telah melihat hal-hal yang saya miliki akan tahu bahwa Irak adalah tempat yang jauh lebih baik," katanya.
Penyerahan kekuasaan AS ke Irak tersebut disambut baik oleh para pemimpin dunia. Uni Eropa dan aliansi NATO sama-sama menjanjikan dukungan mereka untuk pemerintahan Allawi.
Bush dan PM Tony Blair tampaknya satu-satunya pemimpin di KTT NATO saat ini yang tahu transfer kedaulatan akan terjadi lebih awal. Berita itu diungkapkan oleh menteri luar negeri Irak Hoshyar Zebari, berbicara setelah pembicaraan dengan perdana menteri Inggris.